Pada masa Pra-Buddha, sistem patriarki sangat kuat. Wanita dianggap milik kaum pria dan tidak memiliki kebebasan. Demikian pula di masa kolonial Belanda, bangsa kita juga mengalami kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
Dalam artikel “Kondisi Perempuan Pada Masa Kolonial Hindia Belanda Awal Abad 20” dijelaskan bahwa “Seorang gadis bangsawan tingkat rendah sampai atas pada waktu meningkat menjadi remaja, dimasukkan dalam “pingitan” dan tidak boleh keluar rumah lagi. Ini merupakan peraturan adat dan harus ditaati. Selama masa pingitan, semua hubungannya dengan masyarakat luar terputus, sampai pada saat gadis tersebut oleh orang tuanya dikawinkan dengan seorang pria yang bukan pilihannya sendiri dan bahkan seringkali juga belum pernah dikenalnya”.
Sgama Buddha lahir di tengah-tengah pandangan yang menganggap bahwa kaum perempuan diposisikan sebagai kaum “pelengkap” yang tidak memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tentu tidak mudah, karena Buddha memposisikan wanita sama dengan pria.
Hal ini terlihat ketika Mahapajapati Gotami memohon kepada Sang Buddha untuk ditahbiskan menjadi Bhikkhuni. Permohonan itu ditolak Sang Buddha. Mahapajapati Gotami tidak menyerah, dia berjuang dengan dukungan Bhikkhu Ananda beserta 500 wanita yang telah memakai jubah dan mencukur rambutnya. Mereka menghadap kembali kepada Sang Buddha untuk menerimanya menjadi Bhikkhuni. Akhirnya Sang Buddha mengabulkan permohonanya. Namun, dia harus menjalankan syarat khusus (garudhamma) yang tidak dijalankan oleh Bhikkhu Sangha. Dari sinilah awal Agama Buddha mengangkat kedudukan wanita sama dengan pria.
Ajaran Buddha adalah ajaran untuk siapa pun, tanpa membedakan jenis kelamin, maupun status sosial, Sang Buddha tidak mendiskriminasi laki-laki dan perempuan, bahkan status sosial. Sang Buddha memahami bahwa kualitas batin seseorang bukan berdasarkan jenis kelamin, kasta, kelahiran, namun karena perilaku manusia itu sendiri.
Dalam Vasala Sutta, Sang Buddha menjelaskan: “Bukan karena kelahiran orang menjadi sampah. Bukan karena kelahiran pula orang menjadi Brahmana (mulia). Oleh karena perbuatanlah orang menjadi sampah. Oleh karena perbuatan pula orang menjadi Brahmana (mulia)”.
Bahkan, dalam Karaniyametta Sutta, ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa cinta kasih bagaikan seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal. Dari kalimat ini jelas sekali, Sang Buddha memandang bahwa wanita memiliki perasaan cinta kasih yang luar biasa. Wanita bukan hanya sebagi seorang ibu bagi anaknya, namun juga sebagai seorang istri bagi suaminya.
Sang Buddha sudah mengkampanyekan kesetaraan gender jauh sebelum isu kesetaraan gender yang diperbincangkan belakangan ini. Selain dari sutta tersebut di atas, ada sebuah kisah ketika Sang Buddha menegaskan kedudukan wanita bisa saja lebih tinggi dari laki-laki. Yaitu, ketika istri Raja Pasenadi melahirkan anak perempuan.
Saat itu, raja tidak menginginkan anak perempuan, dan kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa “Sebagian wanita adalah lebih baik daripada pria, O Raja. Ada wanita-wanita yang bijaksana, baik, yang menghormati ibu mertuanya, seperti dewa, dan yang tulus dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mereka suatu hari mungkin melahirkan anak laki-laki yang berani yang dapat memerintah kerajaan”.
Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Agama Buddha sangat menjunjung kesetaraan gender. Dalam kehidupan kemasyarakatan, kita saat ini hampir tidak ada batasan perbedaan seorang wanita dalam profesi pekerjaanya. Sebagai contoh, profesi sopir, tukang ojek saat ini juga dilakukan oleh wanita.
Namun, Sang Buddha pernah berpesan kepada Vesaka bahwa wanita akan memiliki kejayaan dan kesuksesan jika memiliki empat kualitas, yaitu: (1) mampu melaksanakan pekerjaanya, (2) mampu mengatur urusan rumah tangga, (3) berprilaku sesuai persetuajuan pasangannya, dan (4) mampu menjaga penghasilan suaminya.
Kesit Sartono, S.Ag (Penyuluh Agama Buddha Kab, Pesawaran, Provinsi Lampung)




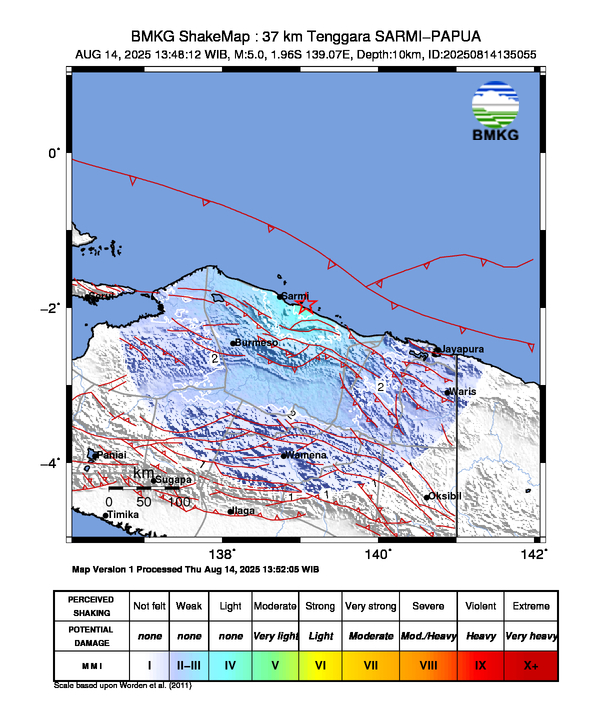
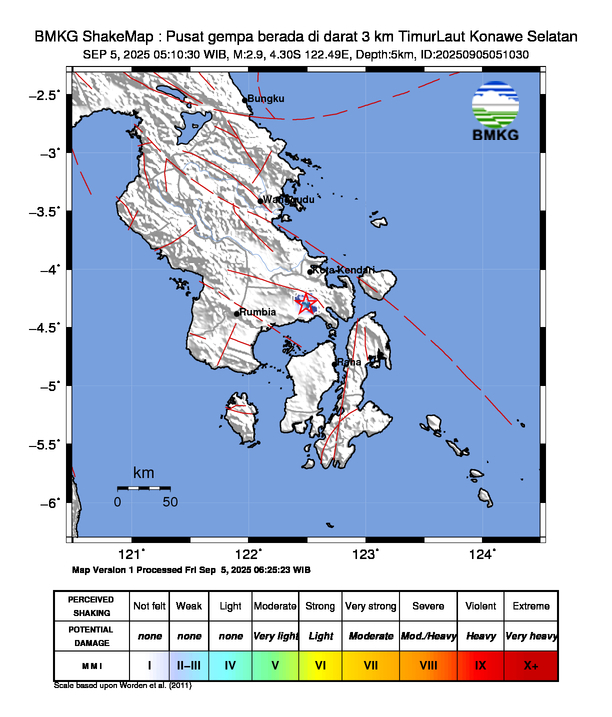


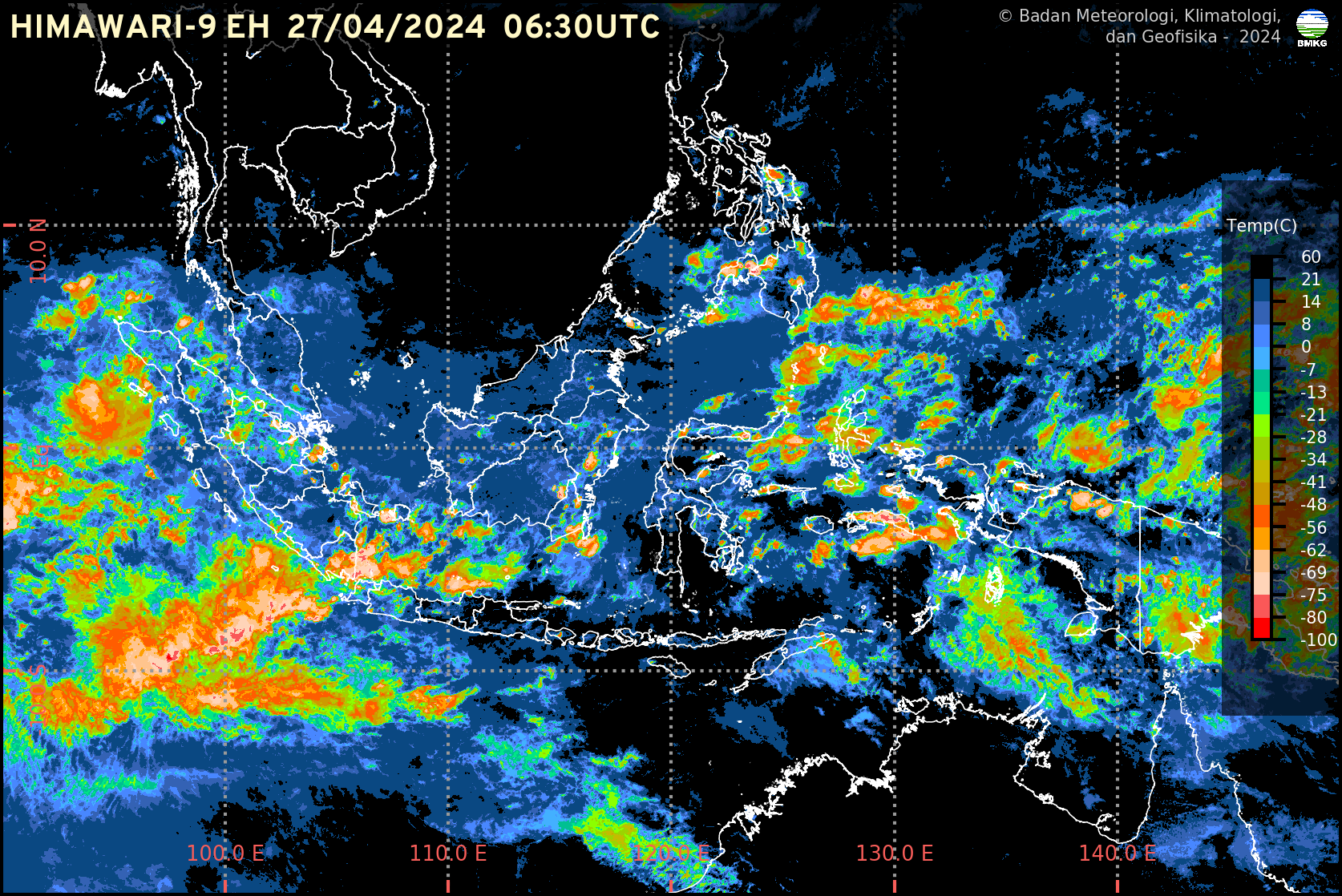








No comments:
Post a Comment